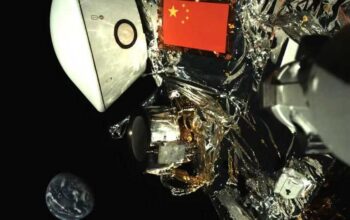Jakarta, Siaran Publik-Arkeoastronomi merupakan disiplin ilmu yang memadukan arkeologi, astronomi, dan antropologi untuk memahami bagaimana manusia masa lampau mempercayai serta memanfaatkan benda-benda langit. Konsep inilah yang dipaparkan oleh Irma Indriana Hariawang, alumni Astronomi Institut Teknologi Bandung (ITB), dalam webinar bertajuk “100 Jam Astronomi untuk Semua” yang digelar oleh Pusat Riset Antariksa (PRA) BRIN, pekan lalu (3/10), dalam rangka memperingati World Space Week 2025.
Irma menjelaskan bahwa arkeoastronomi terbagi dalam tiga cabang utama: astroarkeologi, sejarah astronomi, dan etnoastronomi. Astroarkeologi berfokus pada arsitektur dan lanskap situs-situs kuno yang berkaitan dengan fenomena langit. Sejarah astronomi mempelajari peninggalan tertulis tentang benda langit, sedangkan etnoastronomi menggali keterkaitan budaya masyarakat terhadap fenomena astronomi.
Berbagai situs bersejarah dunia seperti Stonehenge di Inggris, Malta Temple di Malta, Gochang Dolmen di Korea, hingga Piramida Mesir disebut sebagai contoh klasik arkeoastronomi yang menunjukkan keterkaitan antara arsitektur, langit, dan manusia. “Bangunan-bangunan tersebut dibangun dengan memperhitungkan posisi Matahari, Bulan, dan bintang, bahkan berfungsi sebagai penanda waktu alami,” ujar Irma dilansir dari BRIN.
Langit dan Leluhur Nusantara
Irma mengungkapkan, jejak arkeoastronomi juga kuat di Indonesia. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, masyarakat Nusantara telah menggunakan langit sebagai panduan hidup, baik untuk navigasi, menentukan musim tanam, maupun upacara keagamaan.
Langit telah menjadi pemandu kehidupan masyarakat kita sejak lama. Pengaruh astronomi dari Tiongkok, India, Arab, dan Eropa turut membentuk akulturasi budaya yang khas, seperti Kalender Saka, penentuan arah kiblat, hingga Pranoto Mongso, sistem kalender pertanian tradisional Jawa.
Bukti kuat keterkaitan itu dapat dilihat pada Candi Borobudur dan Candi Prambanan, dua warisan megah yang dibangun selaras dengan posisi Matahari dan Bulan. “Pembangunan candi-candi tersebut bukan kebetulan. Nenek moyang kita memahami pergerakan benda langit dan menerapkannya dengan presisi luar biasa,” ujar Irma.
Selain itu, peninggalan seperti Bejana Zodiak di Pasuruan, Gnomon Suku Kenyah Dayak di Kalimantan Timur, dan Bencet di Jawa Tengah menjadi saksi betapa erat hubungan antara langit dan kehidupan masyarakat. Bejana Zodiak bahkan masih bisa disaksikan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.
Potensi Astrowisata dan Teknologi Masa Depan
Irma menilai masih banyak situs arkeoastronomi di Indonesia yang belum terungkap. Ia menekankan pentingnya riset lintas disiplin agar warisan tersebut dapat dikaji lebih dalam dan dikembangkan menjadi astrowisata edukatif yang menarik minat wisatawan dan peneliti.
“Situs-situs ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi jembatan antara sains, budaya, dan spiritualitas. Kolaborasi riset antara astronom, arkeolog, dan antropolog akan membuka pemahaman baru tentang cara leluhur kita memandang alam semesta,” ujarnya.
Irma juga memandang teknologi modern seperti Machine Learning dan Virtual Reality (VR) dapat menjadi sarana untuk menafsirkan ulang peninggalan kuno. “Dengan teknologi itu, publik bisa menyaksikan kembali gerak bintang di atas situs bersejarah dan memahami makna spiritual di baliknya,” pungkasnya.
Arkeoastronomi, menurutnya, bukan hanya tentang sains atau sejarah, tetapi tentang bagaimana manusia memaknai dirinya sebagai bagian dari kosmos. Sebagaimana leluhur Nusantara dahulu, di bawah langit yang sama, manusia modern pun masih mencari arah, makna, dan keterhubungan dengan semesta.(*)